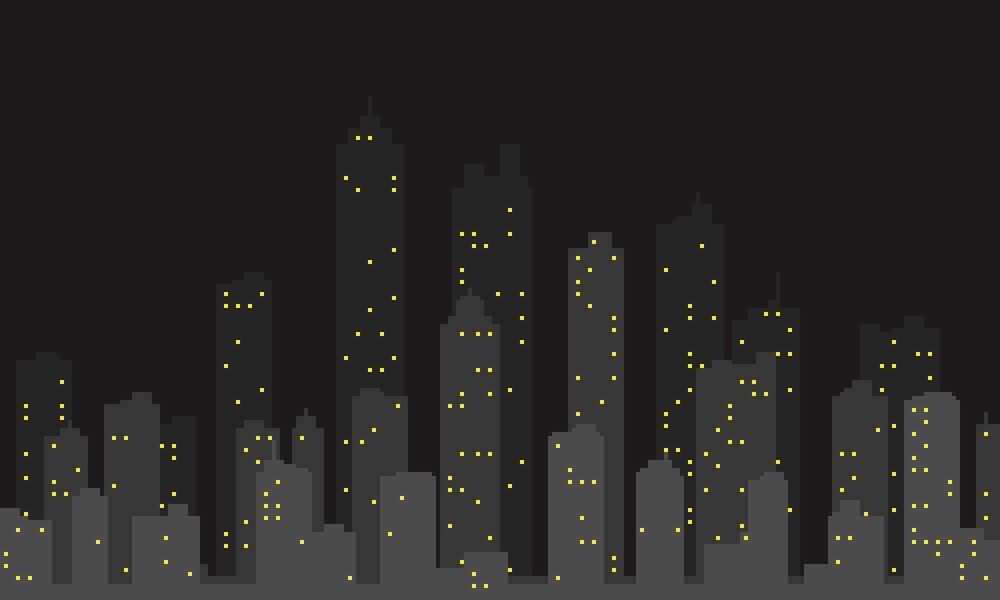CARAPANDANG - oleh Mujamin Jassin
Di saat dunia sastra tengah dikejutkan oleh sebuah novel, karya best seller berisi cerita yang menyentuh hati, inspiratif, mengharukan dan menarik direnungkan. Pada waktu yang tercatat hampir bersamaan tertimpa warta distopia para Kepala Desa datang geruduk berunjuk rasa gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menuntut perpanjangan masa jabatan dari yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun. Selain itu, mereka juga meminta agar jumlah periode jabatan dapat menembus tiga kali jabatan.
Terus terang aku tidak mendambakan apa lagi terbawa larut dalam polemik yang tidak bermutu terkait ide perpanjang jabatan ini, termasuk ambisi buruk tiga periode Presiden, Bukankah hingga kini sama sekali tak senada relevan, tidak sepadan dengan suasana kantor Desa yang hanya ramai, hidup bila sedang ada pembagian sembako atau pada saat foto KTP.
Tak hanya nyeleneh, datang demo dengan gaya cetar membahana, pakai kacamata branded kelas dunia, LV (Louis Vuitton) dan sambil tenteng tas Hermes. Dapat dikatakan keluar jalur, sebab ingin tilep kekuasaan yang lebih lama, sementara menciptakan keindahan Desa yang rapi, bersih, damai dari konflik horizontal, Desa Anti Korupsi sehingga kesejahteraan dan kemakmuran hidup bagi masyarakat desa justru terbilang nihil, meski tak memungkiri ada beberapa Desa cemerlang.
Sampai disini kita bisa pahami, rupanya benar adagium, libido politik memang tak ada batasnya, tidak menua hingga terbawa mati oleh ragawi dan naluri yang memproduksinya, ia hidup dengan instrumen yang sangat subjektif. Tak ada yang bisa diakhiri, kecuali persetujuan pemilih sebagai pemegang Daulat bagi mereka.
Selain tidak produktif sandaran atau lebih tepatnya alibi di dalam arena aksi demo apartur Desa, terselip pula isu santer jabatan Gubernur sebaiknya dihapus saja karena dianggap fungsinya tidak efektif, capek berPilgub dengan anggaran fantastis hanya bagai pos pengantar pesan pusat-daerah. Make sense?! Sebab bila ditiadakan, lantas siapa yang mengelola wilayah provinsi?
Dan yang menyebalkan, aksi dan berita ini melenyapkan kisah pilu seorang bapak muda korban PHK yang mendapat tugas tambahan momong anaknya. Si bapak frustasi mencium bau kencing dan kotoran yang bersumber pada popok sang anak.
Sungguh tak akan ada kasus yang memalukan seperti ini lantaran isteri pujaannya yang ke pasar hanya membawa kucingnya yang gemar menggoda dengan tingkah lucu. Betapa bingung apa yang akan dilakukannya, curhat di facebook, abaikan saja, atau mengurung diri di kamar? Tentu saja ia harus mengganti popok anak kesayangannya, sebab ketahuilah (popok sekali pakai) harus diganti secara rutin, bila menunggu beresiko anak akan mengalami iritasi.
Cuplikan kisah popok, sebagai gerbang pintu pengembaraan filsafat, tiket kita untuk berbulan madu romantis bersama di musiman politik yang mulai memanas kini. Di tengah gencar citra diri mengabaikan etika mengerumuni kita, mereka kemudian terpaksa merubah gaya, dan melengkingkan pidato. Seolah-olah fundamental politik tidak berlingkungan atau bertetangga dekat dengan moral, bersirkulasi udara budaya, bermata nurani dan tak memelihara iman.
Bertolak pada situasi ini yang memiliki korelasi dengan sari pemikiran “politisi popok” dari seorang filsuf, Mark Twain, bermaksud bahwa politisi harus sering diganti seperti popok demi menghindari kesumat politik ingin melulu yang tidak sekedar berpotensi mencederai kohesivitas berbangsa, dan menggoda integritas. "Politisi itu seperti popok, harus sering diganti, kalau tidak akan bau," kata seorang politikus yang barangkali ia merasa telah menjelma gaek politik.
Namun lebih dari itu, politisi popok untuk menjaga kesewenang-wenangan, kekuasaan menjelma totaliter, pelanggengan oligarki dan termasuk menjaga sikap angkuh lupa diri (niretis dan amoral) para politisi. Hal tersebut senada dengan kata Lord Acton, bahwa kekuasaan yang lama berulang-ulang, cenderung salah guna, alami iritasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Mutlak dibatasi, atau berdurasi ganti seperti popok agar juga sistem demokrasi yang berprinsip adil (nondiskriminatif) memberikan kesempatan kepada yang lain mencicipi kekuasaan berjalan secara konsekuen. Terutama jangan lupa supaya dapat membedakan bobot politisi lansia yang berorientasi kekuasaan dengan kepiawaian aplikasi politik yang memfokuskan perhatiannya pada tujuan bagaimana dapat apa, dan berapa.
Penegasan tentang signifikansi politisi, ia menjadi berarti manakala kekuasaan digunakan untuk tujuan keadilan, kemanusiaan dan pembebasan sebagaimana cita-cita religi (Maarif,1984). Rupanya maksud disini, kebebasan berpolitik memang dijamin sepenuhnya secara dimensi prosedural, tetapi mesti juga disertai etik atau berdimensi substansial agar dapat dipertanggungjawabkan. Plato mengkategorikan, mereka yang berhak menjadi penguasa adalah yang mengerti prinsip kebajikan. Apa saja yang dilakukannya haruslah untuk mencapai kebajikan.
Demokrasi alami kemacetan karena dimaknai keliru, penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan, bahkan sampai pada betapapun tercelanya politisi, diberikan kekuasaan besar dan memiliki waktu durasi panjang, lapang serta luang untuk tak memikirkan persoalan-persoalan mendasar kehidupan sosial masyarakat. Artinya sejauh tidak menyentuh kearifan dalam makna kemaslahatan kolektif sebut Aristoteles. Ialah wajar menjadi kesadaran agar tidak membiarkan kekuasaan dikelola oleh politisi yang hanya bicara soal bagaimana dapat apa, dan berapa.
Reformasi tidak bisa lagi diandalkan sebagai trigger pembenahan peradaban, tapi regime Pemilu, Pileg, Pilkada, dan atau Pilkades haruslah diletakkan sebagai babak baru atau pintu masuk untuk perbaikan yang membuahkan hasil. Paradigma negara dan terutama kita semua (pemilik kedaulatan suara) mesti mengarahkan energi pada kesadaran politik rasionalitas yang tidak dicampuri oleh emosionalitas yang meluap dalam Pemilu, Pileg, Pilkada, hingga pada level Pilkades. Sungguh-sunguh memproduksi filsafat yang langka, yakni menciptakan peningkatan kualitas, dan performance politik dari penyalahgunaan kesempatan (monopoli) politisi pesing.

Di saat dunia sastra tengah dikejutkan oleh sebuah novel, karya best seller berisi cerita yang menyentuh hati, inspiratif, mengharukan dan menarik direnungkan. Pada waktu yang tercatat hampir bersamaan tertimpa warta distopia para Kepala Desa datang geruduk berunjuk rasa gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menuntut perpanjangan masa jabatan dari yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun. Selain itu, mereka juga meminta agar jumlah periode jabatan dapat menembus tiga kali jabatan.
Terus terang aku tidak mendambakan apa lagi terbawa larut dalam polemik yang tidak bermutu terkait ide perpanjang jabatan ini, termasuk ambisi buruk tiga periode Presiden, Bukankah hingga kini sama sekali tak senada relevan, tidak sepadan dengan suasana kantor Desa yang hanya ramai, hidup bila sedang ada pembagian sembako atau pada saat foto KTP.
Tak hanya nyeleneh, datang demo dengan gaya cetar membahana, pakai kacamata branded kelas dunia, LV (Louis Vuitton) dan sambil tenteng tas Hermes. Dapat dikatakan keluar jalur, sebab ingin tilep kekuasaan yang lebih lama, sementara menciptakan keindahan Desa yang rapi, bersih, damai dari konflik horizontal, Desa Anti Korupsi sehingga kesejahteraan dan kemakmuran hidup bagi masyarakat desa justru terbilang nihil, meski tak memungkiri ada beberapa Desa cemerlang.
Sampai disini kita bisa pahami, rupanya benar adagium, libido politik memang tak ada batasnya, tidak menua hingga terbawa mati oleh ragawi dan naluri yang memproduksinya, ia hidup dengan instrumen yang sangat subjektif. Tak ada yang bisa diakhiri, kecuali persetujuan pemilih sebagai pemegang Daulat bagi mereka.
Selain tidak produktif sandaran atau lebih tepatnya alibi di dalam arena aksi demo apartur Desa, terselip pula isu santer jabatan Gubernur sebaiknya dihapus saja karena dianggap fungsinya tidak efektif, capek berPilgub dengan anggaran fantastis hanya bagai pos pengantar pesan pusat-daerah. Make sense?! Sebab bila ditiadakan, lantas siapa yang mengelola wilayah provinsi?
Dan yang menyebalkan, aksi dan berita ini melenyapkan kisah pilu seorang bapak muda korban PHK yang mendapat tugas tambahan momong anaknya. Si bapak frustasi mencium bau kencing dan kotoran yang bersumber pada popok sang anak.
Sungguh tak akan ada kasus yang memalukan seperti ini lantaran isteri pujaannya yang ke pasar hanya membawa kucingnya yang gemar menggoda dengan tingkah lucu. Betapa bingung apa yang akan dilakukannya, curhat di facebook, abaikan saja, atau mengurung diri di kamar? Tentu saja ia harus mengganti popok anak kesayangannya, sebab ketahuilah (popok sekali pakai) harus diganti secara rutin, bila menunggu beresiko anak akan mengalami iritasi.
Cuplikan kisah popok, sebagai gerbang pintu pengembaraan filsafat, tiket kita untuk berbulan madu romantis bersama di musiman politik yang mulai memanas kini. Di tengah gencar citra diri mengabaikan etika mengerumuni kita, mereka kemudian terpaksa merubah gaya, dan melengkingkan pidato. Seolah-olah fundamental politik tidak berlingkungan atau bertetangga dekat dengan moral, bersirkulasi udara budaya, bermata nurani dan tak memelihara iman.
Bertolak pada situasi ini yang memiliki korelasi dengan sari pemikiran “politisi popok” dari seorang filsuf, Mark Twain, bermaksud bahwa politisi harus sering diganti seperti popok demi menghindari kesumat politik ingin melulu yang tidak sekedar berpotensi mencederai kohesivitas berbangsa, dan menggoda integritas. "Politisi itu seperti popok, harus sering diganti, kalau tidak akan bau," kata seorang politikus yang barangkali ia merasa telah menjelma gaek politik.
Namun lebih dari itu, politisi popok untuk menjaga kesewenang-wenangan, kekuasaan menjelma totaliter, pelanggengan oligarki dan termasuk menjaga sikap angkuh lupa diri (niretis dan amoral) para politisi. Hal tersebut senada dengan kata Lord Acton, bahwa kekuasaan yang lama berulang-ulang, cenderung salah guna, alami iritasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Mutlak dibatasi, atau berdurasi ganti seperti popok agar juga sistem demokrasi yang berprinsip adil (nondiskriminatif) memberikan kesempatan kepada yang lain mencicipi kekuasaan berjalan secara konsekuen. Terutama jangan lupa supaya dapat membedakan bobot politisi lansia yang berorientasi kekuasaan dengan kepiawaian aplikasi politik yang memfokuskan perhatiannya pada tujuan bagaimana dapat apa, dan berapa.
Penegasan tentang signifikansi politisi, ia menjadi berarti manakala kekuasaan digunakan untuk tujuan keadilan, kemanusiaan dan pembebasan sebagaimana cita-cita religi (Maarif,1984). Rupanya maksud disini, kebebasan berpolitik memang dijamin sepenuhnya secara dimensi prosedural, tetapi mesti juga disertai etik atau berdimensi substansial agar dapat dipertanggungjawabkan. Plato mengkategorikan, mereka yang berhak menjadi penguasa adalah yang mengerti prinsip kebajikan. Apa saja yang dilakukannya haruslah untuk mencapai kebajikan.
Demokrasi alami kemacetan karena dimaknai keliru, penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan, bahkan sampai pada betapapun tercelanya politisi, diberikan kekuasaan besar dan memiliki waktu durasi panjang, lapang serta luang untuk tak memikirkan persoalan-persoalan mendasar kehidupan sosial masyarakat. Artinya sejauh tidak menyentuh kearifan dalam makna kemaslahatan kolektif sebut Aristoteles. Ialah wajar menjadi kesadaran agar tidak membiarkan kekuasaan dikelola oleh politisi yang hanya bicara soal bagaimana dapat apa, dan berapa.
Reformasi tidak bisa lagi diandalkan sebagai trigger pembenahan peradaban, tapi regime Pemilu, Pileg, Pilkada, dan atau Pilkades haruslah diletakkan sebagai babak baru atau pintu masuk untuk perbaikan yang membuahkan hasil. Paradigma negara dan terutama kita semua (pemilik kedaulatan suara) mesti mengarahkan energi pada kesadaran politik rasionalitas yang tidak dicampuri oleh emosionalitas yang meluap dalam Pemilu, Pileg, Pilkada, hingga pada level Pilkades. Sungguh-sunguh memproduksi filsafat yang langka, yakni menciptakan peningkatan kualitas, dan performance politik dari penyalahgunaan kesempatan (monopoli) politisi pesing.